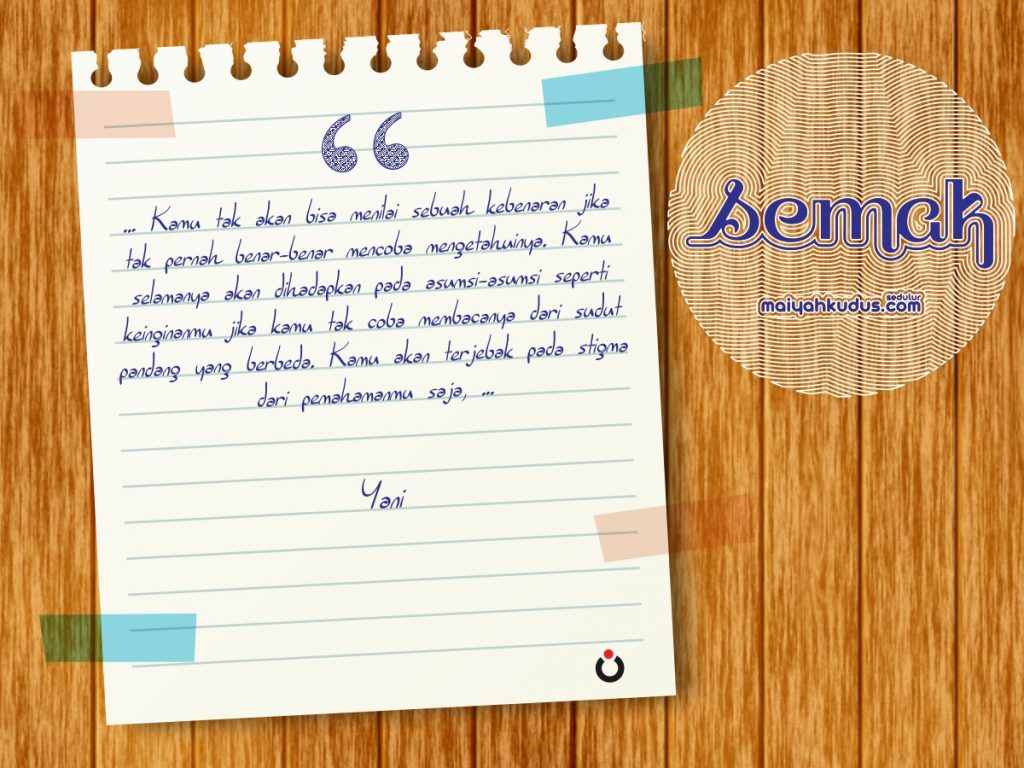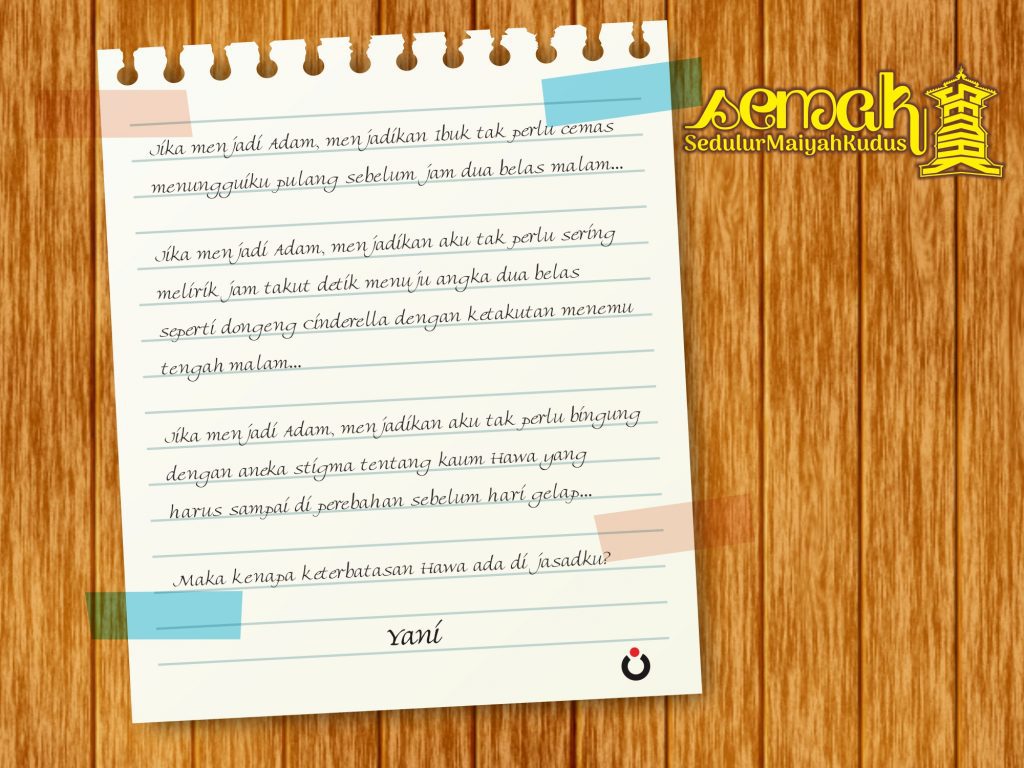“Sayangnya di maiyah tak benar-benar dihadiri oleh Cak Nun. Pembahasan di majlis itu menyoal apa? Politik, kah? Sosial? Ekonomi? Atau religiusitas?” Mas Sabil mendaratkan tanya.
“Apa saja yang bisa dibahas serta didiskusikan, Mas.” Tak kuperpanjang jawaban itu, bukan tak ingin. Namun, apakah dari deretan pertanyaan itu ia benar-benar membutuhkan jawaban? Atau sebatas tanya menguji kadar kemilitanku pada si Mbah? Militan? Apakah kata itu tepat? Aku rasa tak ada sebutan ekstrim atas pelaku maiyah dalam menamai dirinya. Hanya aku pernah baca, bahwa…
“Maiyah itu organisme, Mas.”
“Opo kuwi, Nduk?”
“Ah, Mas Sabil bisa jadi tak benar-benar ingin mengetahui maiyah. Menjabarkan dengan kalimat akan tetap kurang merasuk pemahaman jika Mas Sabil belum ikut duduk bersama dalam majlis itu.”
“Owalah…. Kamu ngajak aku ikut maiyahan tho, Nduk?”
“Bukan begitu maksud saya, Mas.”
“Naaah… Itu pipimu memerah, kamu ini lho, mbok ya bilang saja. Mas ndak keberatan kalau kamu minta Mas ngantar ke maiyahan.”
“Maksud Ai ndak gitu. Mas kliru nampi omongan saya. Mpun nggih, Mas. Ai motongin kertas kalau kelewat garis malah repot mengulang nge-print lagi.”
Sebenarnya hendak kujelaskan bahwa kata ‘organisme’ yang dimaksud adalah satu bentuk, struktur kehidupan yang tersusun atas bagian-bagian yang sangat banyak dan saling terkait satu sama lain. Sehingga, salah satu ciri utama dari organisme adalah keterkaitan dan saling keterkaitan. Setiap langkah diandalkan akan memiliki kaitan atau sentuhan pada bagian-bagian lain, baik kaitan itu bersifat ilmu, moral, maupun nilai-nilai lainnya. Aku ingat, dan merekamnya di memori ketika membaca sebuah tulisan tentang maiyah di situs resmi official Mbah Nun.
Tapi aku sangsi pada tiap tanya Mas Sabil. Seperti bukan kemurnian pertanyaan tetapi lebih bagaimana caranya agar intens berkomunikasi padaku. Maksudnya, jika ‘rumongso Ge-Er’itu tidak dilarang. Aku memang merasa seperti itu tepatnya. Sekarang arus informasi sudah berkembang kian pesatnya. Bukankah ia juga bisa bertanya pada mesin pencarian google yang lebih komplit?
Tak kupungkiri… Mas Sabil baik, namun untuk menjadi orang yang masuk dalam kehidupan seorang ‘Sekar’ tak cukup hanya memiliki sifat baik. Apakah aku sombong? Tidak! Justru aku takut lelaki yang mencoba mendekatiku tak benar-benar siap dengan keadaanku yang bisa dibilang ‘menyedihkan’. Ah, itu kiasan yang aku buat untuk mengumpamakan nasibku sebagai seorang anak dari keluarga ‘brokenhome’. Di situlah tak cukup kata ‘baik’ untuk menerima seorang Sekar.
Dan tentunya, Sekar bukanlah bunga yang indah. Aku bukan sosok menantu yang diidamkan banyak ibu mertua. Aku bukan wanita hebat yang bisa dibanggakan dalam karir. Aku bukan wanita religius yang mengerti betul kajian-kajian kitab kuning tentang mencari surga dalam menjadi istri. Aku masih berharap tak memiliki nama itu ketika lahir. Tapi nama adalah doa, Ibuk dan Bapak dulu tak mungkin tanpa harapan, berkeinginan bayi perempuannya akan secantik bunga. Harum lakunya, atau… pengibaratan yang itu-itu saja tentang kembang. Pengumpamaan yang melangit tentang kembang, yang ada malah Sekar tak bisa menjawab tuntutan doa pada nama itu. Biarlah…
“Nduk…” Pesan singkat dari nomor yang belum aku simpan di kontak whatsapp.
“Nduk…” Kali kedua pesan itu masih urung kubalas.
“Ini Bapak. Sore ini Bapak benar-benar ingin kamu datang ke rumah. Bu Lik Ana juga berharap kamu dapat memenuhi undangan ini.”
Bapak? Benarkah ini Bapak? Bu Lik Ana itu siapa? Apakah istri Bapak?
“Tak tanglet Ibuk nggih, Pak.” Sebuah kalimat aku ketik, aku baca, hendak kutekan tombol send. Tapi aku delete lagi.
“Nduk… Kamu sudah membacanya, kan? Kenapa ndak balas? Bapak rindu Ai. Sebutan Ai itu… Tahukah kamu, Nduk? Dulu lidahmu belum fasih mengucap namamu sendiri. Sehingga Ibukmu, Kakang-kakangmu, dan Bapak ikut memanggilmu demikian.”
Ah, penjelasan sama yang sering Ibuk ceritakan tentang namaku. Sama persis… Apakah dulu Bapak dan Ibu benar-benar menjadi tim yang solid dalam merawatku?
“Bapaaak…. Bapak mau cerita apa tentang masa kecil Ai? Ceritalah…” Lagi, setelah kuketik, entah mengapa wajah Ibuk terpampang jelas di bayangan. Ibuk tak akan rela, Ibuk tak ingin aku menemui Bapak setelah meninggalkan kami lama. Ibuk tak akan restu dengan obrolan ini walau hanya lewat pesan.
“Nduk… Bapak salah, tapi di antara kita tak pernah ada penjelasan. Tepatnya, Ibukmu tak pernah mengijinkan Bapak menjelaskan akan kepergian Bapak dulu. Bapak hanya boleh menemui Ibukmu sambil diijinkan meninggalkan pesan untuk kamu dan Kakangmu. Tapi pesan itu entah sampai entah tidak.” Kubaca pesan itu dari huruf per hurufnya. Ini tulisan lelaki yang darah serta dagingnya ada pada tubuhku. Lelaki yang akan menjadi wali ketika pada waktu yang entah akan ada Adam yang menikahiku. Lelaki yang tak terputus ikatan walau sejauh apa bumi memisah, atau keadaan mencipta jarak. Aku lahir atas benihnya dalam rahim Ibuk. Mustahil Ibuk tak pernah cinta. Bahwa yang aku tangkap adalah kebencian Ibuk pada Bapak mungkin akibat dari sebuah kekecewaan. Tetapi… Aku tidak pernah memiliki detik untuk mendengarkan penjelasan apapun. Bahkan untuk bertemu. Pesan Ibuk hanya, Bapak mengijinkanku ke rumahnya kapanpun untuk minta uang. Tapi Ibuk tak benar-benar menganjurkan aku meminta uang pada Bapak. Bahkan malah mengisyaratkan ‘Jangan, Ibuk bisa membiayai kebutuhan Ai’. Entahlah… Rumah Bapakpun sebuah rahasia yang tak pernah Ibuk sematkan sebagai tempat yang akan aku jejaki. Tidak pernah. Semuanya terbungkus dalam kerahasiaan. Tak ada foto wajah Bapak di rumah kami. Hanya ketika aku main ke rumah Kang Apar, kakakku yang pertama, aku melihat foto pernikahan Ibuk dan Bapak dengan kebaya sederhana tanpa dekorasi serta riasan.
“Ini Bapak kita, Ai. Suatu saat kalau kamu siap, Kang Apar akan membawamu menemui Bapak.” Aku ingat Kang Apar pernah berkata itu. Dua nama kakang-kakangku juga pemberian dari Bapak. Kata Kang Apar, namanya, Ja’far Shodiq diilhami Bapak dari ketokohan nama Sunan Kudus. Begitu juga kakangku yang kedua, Kang Umar ialah nama yang diambil dari nama Sunan Muria, Raden Umar Said.
“Sedangkan namamu murni dari Ibuk, Ai…” Kang Apar berkata demikian saat aku pernah menanyakan.
Ah, suara ponselku berbunyi lagi.
“Nduk… Kamu tak akan bisa menilai sebuah kebenaran jika tak pernah benar-benar mencoba mengetahuinya. Kamu selamanya akan dihadapkan pada asumsi-asumsi seperti keinginanmu jika kamu tak coba membacanya dari sudut pandang yang berbeda. Kamu akan terjebak pada stigma dari pemahamanmu saja, Nduk. Sudah lama Bapak ingin mengajakmu minum kopi. Tapi… Bapak bahkan tidak tahu kamu suka kopi atau tidak.”
“Lagi, Bapak… Silahkan ketik apapun. Mungkin jika Ibuk tak restu kita berkomunikasi. Setelahnya aku akan melayangkan maaf. Tuhan juga sesuai sangkaan hamba-Nya. Maka ketika aku menyangka Tuhan memberi pengecualian atas ini, aku rasa sangkaan itu diiyakan Tuhan.” Ah, ketikan apa ini? Aku bahkan tak tahu watak Bapak seperti apa. Maka sebelum berniat menekan tombol kirim (lagi), pilihan tetap pada tombol hapus. Dan tak ada satu pesan pun yang aku balas untuk Bapak. Tombol hapus menguasai sistem perintah pada sarafku.
“Nduk… Seorang Sekar tidak akan menilai Bapak dari ‘katanya’. Bapak yakin itu. Bisakah kamu datang, Nduk? Bisakah?”
Bapak, nama yang asing. Sebutan yang tak pernah kuucap, kali ini kurasakan tiap ketikannya seperti merasuk dan aku tak merasakan bahwa yang mengetik ini orang asing. Ia Bapakku. Pemikiran tentang ‘sudut pandang dalam pemahaman’, bahkan itu bukan sesuatu yang asing aku dapat di maiyah. Bapak… Di tubuhku mengalir darah Bapak. Aku yakin Bapak bukan lelaki tak baik seperti framing yang melekat padaku. Andai kita punya banyak waktu bicara…
Berat untuk tidak menangis. Dan saat sisi cengeng itu muncul, aku lupa bahwa tadi Mas Sabil memperhatikan raut mukaku yang mendrama. Ia tak bertanya secerewet ketika menanyakan perihal maiyah. Ia memilih membiarkanku memandangi layar ponsel tanpa sedikitpun memulai tanya. Kini bulir air mata itu tak bisa berdiam di tempat yang mula. Memilih menderas membunyikan isak. Ini tempat kerja. Suasana memang tidak ramai. Tak ada pelanggan. Lik Topo juga belum datang. Aku tak mau Mas Sabil membaca ledakan tangisku. Aku tak mau mencipta scene di sinetron bahwa ada lelaki yang menenangkan tangis seorang Sekar. Lagi, aku Semak. Bukan Sekar. Aku tahan pada cuaca apapun, aku tahan pada sebadai apa angin, aku tahan pada sepanas apa musim.
“Sekar???”
“Mas, titip kunci tempat ini, nggih… Nanti kalau Lik Topo datang, tolong bilang bahwa Sekar di We-A Ibuk. Sekar pamit.”