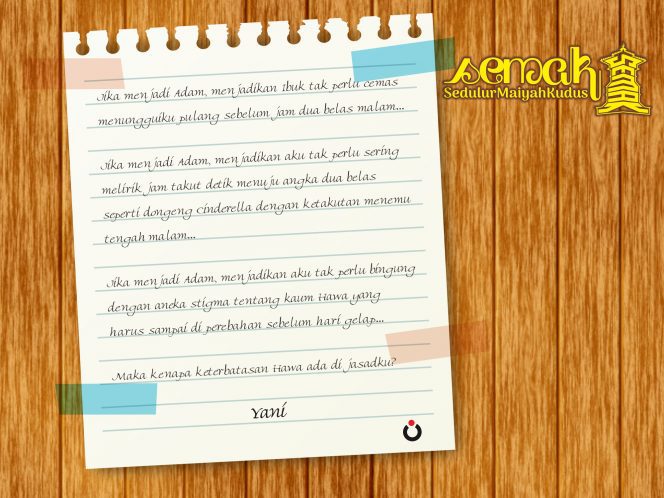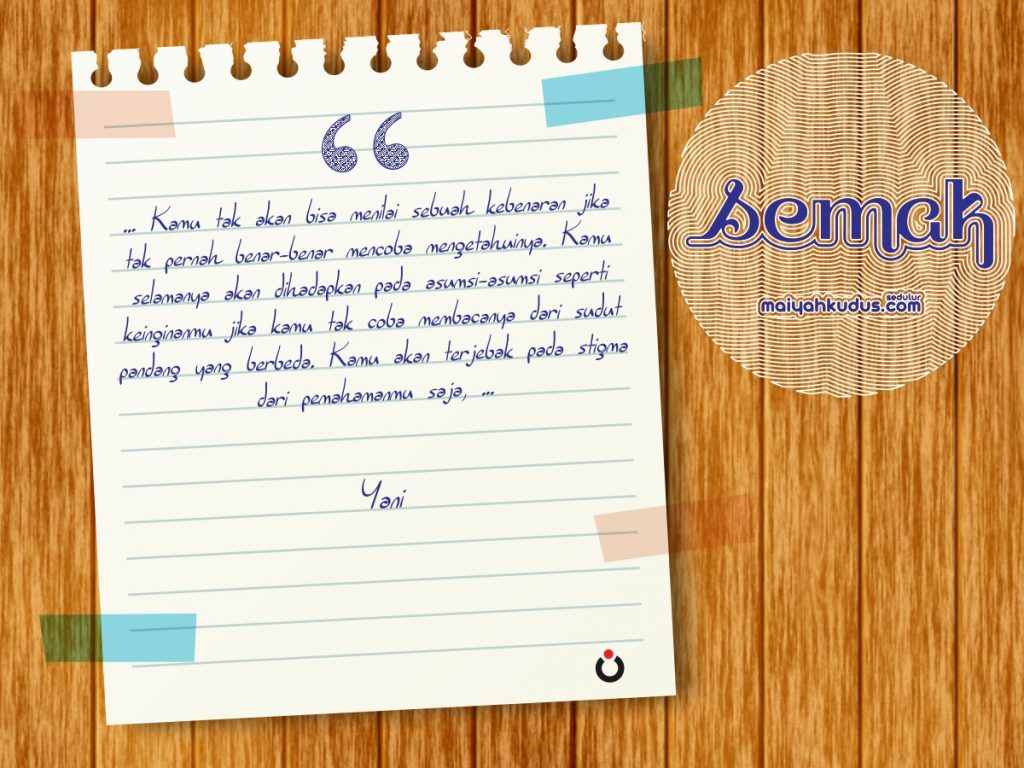Meminta menjadi lelaki adalah mustahil. Namaku Sekar, tanpa embel-embel apapun. Kata Ibuk berarti ‘bunga’. Tapi aku tak suka bunga. Nama yang sekiranya terlalu memiliki pengharapan tinggi bahwa aku akan jadi seperti bunga, anggun, feminim, serta alus.
“Arep maiyahan kamu, Ai?” tanya Ibuk menghitung bathi dodolan tadi siang. Aku tak menjawab, hanya menghampiri raga yang berusia lima puluhan itu sembari mengecup telapak tangannya.
Ibuk, Kang Apar, dan Kang Umar sedari kecil biasa menggunakan mana panggilan ‘Ai’ untukku. Bagaimana dengan Bapak? Entahlah, belum banyak aku ingin berkisah tentang Bapak. Bukan tak akan dan tak ingin. Mungkin nanti, atau kapan.
“Wong wadhon ora ilok mulih wengi.”
“Ai niatnya sinau, Buk.”
“Sinau bisa lewat jalan manapun, Nduk. Lha kamu bakdal Isya ngaji ke tempat Yai Ghopur juga bisa. Gabung sama anak pondok maknani kitab kuning. Tapi ya… Ibuk ndak bisa mbayar kalau kamu minta mondok. Bisane ngasih gulo kopi seminggu sekali ke Yai Ghopur.”
“Ai pamit maiyahan nggih, Buk.”
“Ya wis, jam sepuluh mulih.”
“Jam sepuluh baru masuk diskusi, Buk.”
“Opo kuwi?”
“Diskusi, semacam bertukar pemahaman.”
“Ngaji opo bertukar pemahaman?”
“Sinau, Buk.”
“Ya wislah, Ibuk ki wong gendheng. Tapi Ibuk juga was-was misale kamu terjerumus kelompok terorisme kayak yang Kaji Dullah sampaikan di ceramahnya. Ibuk ini sudah tua. Ndak tahu pergaulanmu kayak apa. Ibuk juga orang bodoh. Kaji Dullah cuma pesan sama jama’ahnya kalau sekarang anak muda itu mudah dirasuki terorisme.”
“Alhamdulillah Ai sinau, ngaji, menjernihkan fikir, Buk. Di maiyah Ai mendapatkan itu. Tapi untuk pulang jam sepuluh sepertinya tidak. Jam dua belas angsal nggih, Buk?”
“Sudah Ibuk tebak.”
“Angsal nggih, Buk?”
Kubaca anggukan kepala setengah berat dari perempuan yang telah melahirkanku dua puluh dua tahun lalu.
“Assalamu’alaikum, Buk.”
“Jo lali, jangan lebih jam dua belas. Akeh setane.”
“Nggih, Buk. Insya Allah.”
“Oh ya, Nduk…”
“Nopo, Buk?”
“Wa’alaikum Salam. Ibuk lali jawab.”
“Nggih.”
“Lha ngopo nggah nggih nggah nggih? Budhalono.”
Aku mengecup telapak tangan itu lagi. Kemudian menyalakan tombol start pada matic yang aku beli kredit dengan tabungan kerja di fotokopi Lik Topo. Ada juga upah menjualkan laptop anak-anak kampus IAIN. Atau sering juga ketika musim mahasiswa akhir mengerjakan skripsi, aku diminta mengerjakan. Kadang puisi atau cerpenku ketika termuat di koran, sedikit banyak juga membantu. Sekarang sudah tahun ketiga angsuran, Bapak pernah menawariku jika butuh uang datanglah. Hanya saja aku takut kemunculanku di rumahnya mendatangkan tekanan psikologis sendiri bagi wanita yang telah dinikahinya semenjak usiaku belum genap sepuluh tahun.
“Kamu ojo sekali-kali datang ke Bapakmu njaluk duwit. Hidup secukupnya, Ibuk sebisa mungkin memenuhi kebutuhan kamu. Jangan iri anak kuliahan, Nduk. Kamu juga jangan sampai minta uang sama kakang-kakangmu. Walaupun saudara, mereka punya tanggungan anak istri. Kakangmu juga dudu wong sugih.”
Kalimat itu yang sering Ibuk katakan padaku. Lantaran itulah aku kuat.
Namaku Sekar
Tapi aku bukan bunga
Bunga hanyalah kiasan bagi putri cantik yang anggun
Namaku Sekar
Tapi aku tak suka sekar atau kembang
Aku lebih ingin bila ada yang menjulikiku ‘semak’
Semak tumbuh tanpa vas
Semak tumbuh tanpa perawatan
Dari segala musim, semak mengakar
Di banyak tempat, semak bertahan hidup
Semak, seperti nama sebuah majelis yang sekarang menjadi rumah tempatku mengeja hidup. Aku tak mengetahui banyak apa itu semak. Setahuku akronim dari ‘Sedulur Maiyah Kudus’, di mana mereka berusaha menjadi cermin. Belajar bersama tanpa mencari sebuah pembenaran. Semua orang guru, semua manusia bisa kita serap ilmu.
“Maiyah itu fans Cak Nun ya, Nduk?” tanya Mas Sabil. Ia adalah juga kawan Lik Topo yang sering dipanggil mereparasi mesin fotokopi, printer, bahkan perangkat komputer serta laptop. Mas Sabil inilah yang sering memergokiku membaca buku Mbah Nun di tempat kerja. Ia juga sering mengomentari story-ku ketika mengikuti majelis Maiyah.
“Tepatnya bukan fans, Mas.”
“Fanatis banget gitu, Kok.” balas Mas Sabil.
Tak kujawab. Aku selalu ringkih bila lama-lama berbincang dengan Mas Sabil. Bukan apa, lantaran tak enak dengan Lik Topo kalau kerja hanya njagong. Sebisanya aku jawab singkat tiap lelaki lulusan Qudsiyah serta teknik Elektro Universitas Muria Kudus itu menanyaiku.
“Pemahaman dan cara beliau mengedepankan dialektika empati yang saya ambil, Mas.”
“Wah wah wah, bahasamu dhuwur, Nduk. Haruse kamu melanjutkan kuliah lho. Lulusan Aliyah wae dhuwur ngene bahasane.”
“Mpun nggih, Mas. Sekarniki ngetik rentalan. Mas Sabil kalau nanya terus nanti ndak selesai-selesai.”
Itu cuma alibiku. Membincang kuliah adalah mimpi yang harus kuurungkan. Paling tidak aku bahagia dengan keadaan sekarang. Maksudnya, mencoba bahagia…
Ada banyak hal tentang maiyah yang ingin aku tulis. Aku bukan penulis, terlalu tinggi bila mengaku demikian. Aku hanya penuang apa yang ada di kepalaku. Dari tulisan, aku bisa berbicara. Mungkin salah satunya Mas Sabil nanti yang akan membaca tulisanku tentang maiyah. Tepatnya, mungkin… Juga banyak yang ingin aku tulis tentang seorang Sekar yang ingin terbang sebebas Adam. Sepertinya kromosom XY ada padaku. Entahlah…
Jika menjadi Adam, menjadikan Ibuk tak perlu cemas menungguiku pulang sebelum jam dua belas malam…
Jika menjadi Adam, menjadikan aku tak perlu sering melirik jam takut detik menuju angka dua belas seperti dongeng Cinderella dengan ketakutan menemu tengah malam…
Jika menjadi Adam, menjadikan aku tak perlu bingung dengan aneka stigma tentang kaum Hawa yang harus sampai di perebahan sebelum hari gelap…
Maka kenapa keterbatasan Hawa ada di jasadku?
“Nduk, ceritakan padaku banyak tentang maiyah.”
Sebuah pesan singkat dari Mas Sabil membalas story WA-ku yang menulis bahwa usai mengecup tangan Ibuk, aku menuju ke majelis maiyah bersama kawan perempuan yang jumlahnya satuan. Paket data bergegas kumatikan. Tak kubalas. Bukan tak berniat, bahkan menunggu pesannya saja kadang serupa jarum jam tertahan.
Ah, ini tak penting juga sebenarnya. Hanya saja menghemat batere lebih aku utamakan karena android inilah yang nanti kujadikan rangkuman-rangkuman penting. Paling tidak untukku sendiri, bukan untuk publikasi. Arsip…. Ya, arsip. Aku masih buta majelis sinau ini. Masih banyak hal belum aku selami.